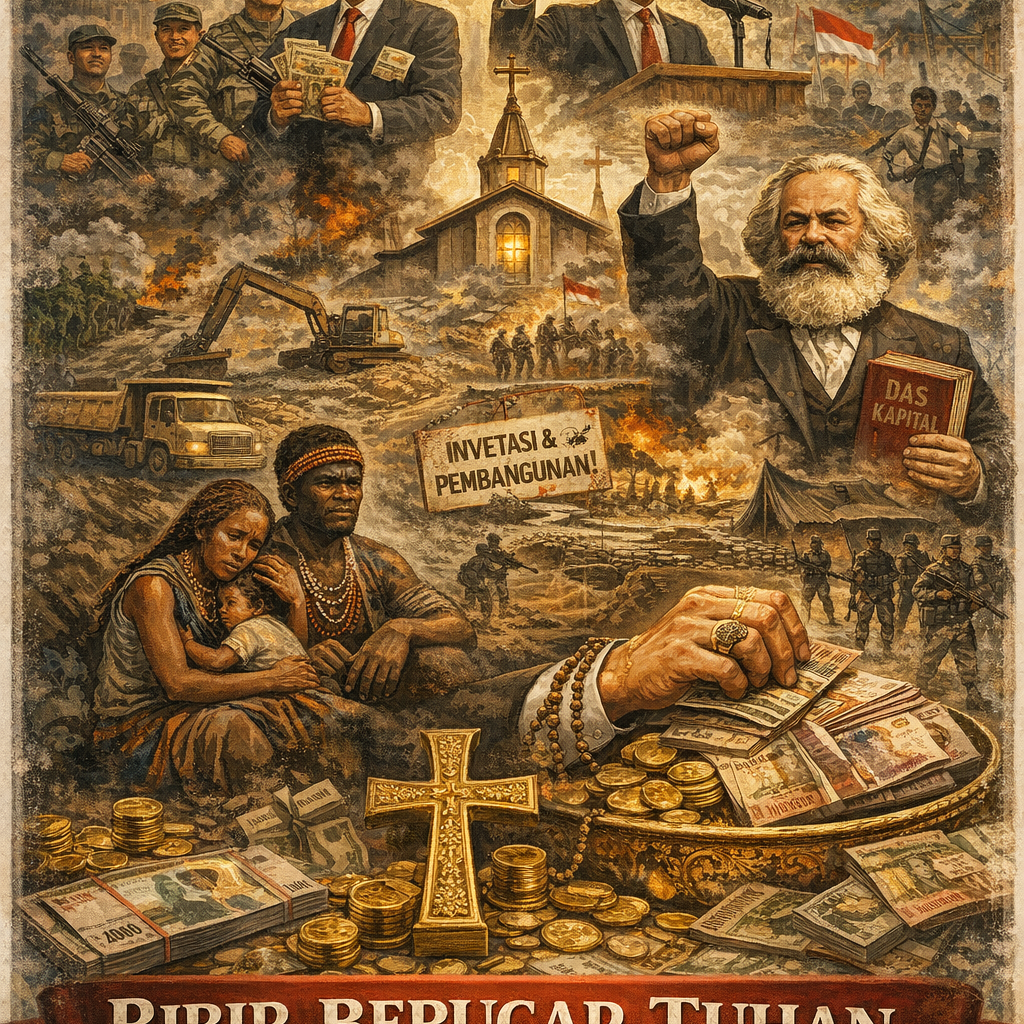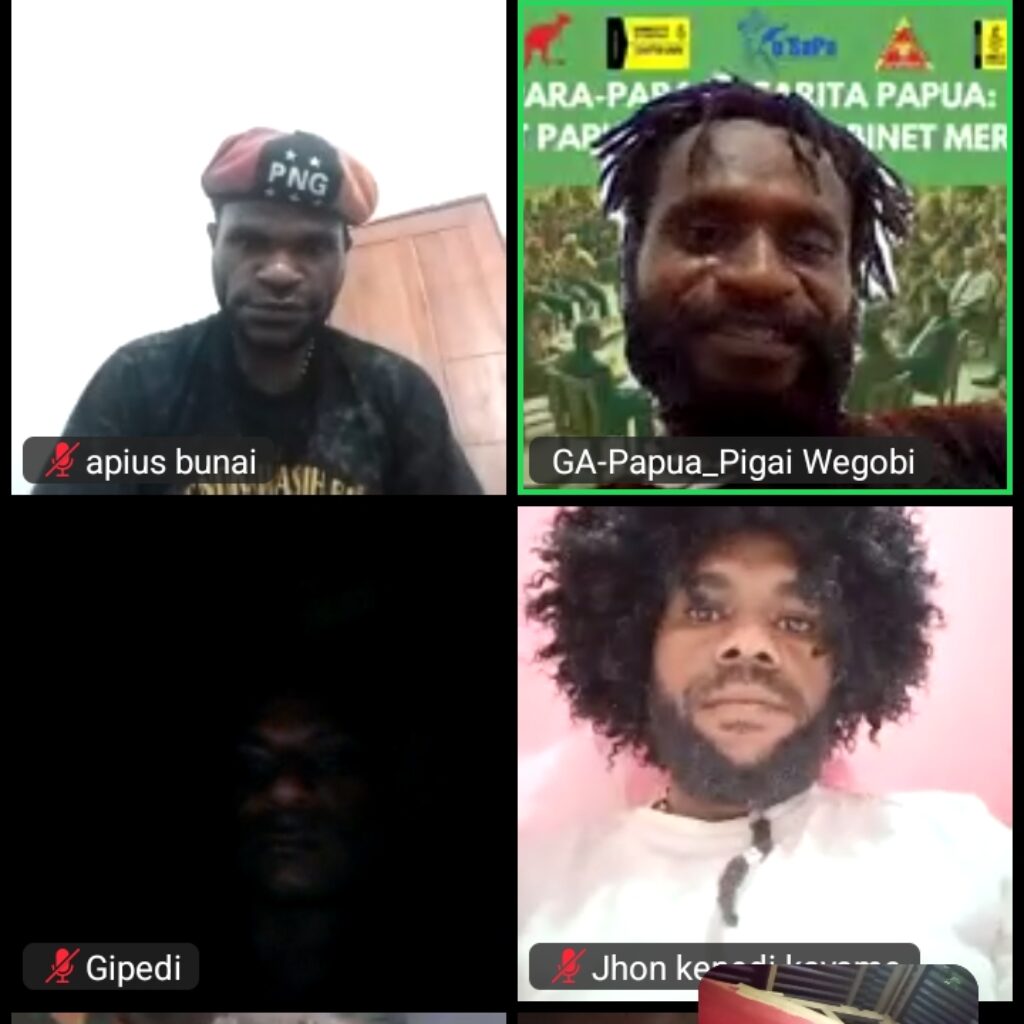Oleh: Jhon Minggus Keiya
Pagi ini, sekitar pukul tujuh lewat lima puluh tujuh menit, saya bersiap berangkat ke tempat kerja dari rumah di Waroki, kilometer lima. Udara pagi masih segar, dan embun di dedaunan belum sepenuhnya menguap. Saya menyalakan motor dan mulai melaju perlahan melewati jalan Waroki yang sebagian besar masih belum diaspal. Lubang-lubang kecil dan batu-batu kerikil memaksa saya untuk berhati-hati. Syukurlah, karena masih pagi, jalan belum ramai dan udara belum dipenuhi polusi maupun debu.
Sesampainya di Pantai Nabire, saya sempat mengubah rencana. Ketika melihat jam di layar ponsel, waktu sudah menunjukkan pukul delapan lewat lima menit. Saya sadar bahwa jika meneruskan jalan yang biasa saya lalui, saya mungkin akan terlambat tiba di kantor.
Akhirnya, saya memutar arah dan memilih jalan Oyehe, kemudian melaju hingga tiba di Tugu Cenderawasih. Dari sana, saya teruskan perjalanan menuju Hotel Karya Papua, tempat dimana sebuah kegiatan RAKOR dari dinas pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan.
Setiba di hotel, saya memarkirkan motor di halaman depan dan segera masuk ke ruang VIP, tempat kegiatan sedang dipersiapkan. Teman-teman panitia sudah sibuk menata perlengkapan dan memeriksa berkas kegiatan. Saya bergabung bersama mereka beberapa menit.
Beberapa menit kemudian, ponsel milik seorang rekan kerja bernama Pace Mas Bagas tiba-tiba berdering. Suara nada dering itu memecah kesunyian ruangan yang saat itu masih dipenuhi kesibukan panitia mempersiapkan acara. Bagas segera mengangkat panggilan itu.
“Halo, Ibu. Selamat pagi,” sapanya sopan.
Ia melanjutkan merespon panggilan di ponselnya. “Yang ada Jhon dan Oti?”
Saya spontan menoleh ke arah Bagas, sedikit terkejut mendengar nama saya disebut. “Lho, kok nama saya disebut ya?” bisik saya pelan kepadanya.
Bagas menatap saya sambil menempelkan satu jari di bibir, memberi isyarat agar saya tenang. Setelah beberapa detik mendengarkan, ia menutup telepon lalu menghampiri saya.
“Jhon, Isak, kalian disuruh ke kantor. Ibu Kadis panggil katanya,” ucapnya dengan nada agak tergesa.
Saya sempat ragu sejenak. “Tapi Isak belum ada,” jawabku pelan, menoleh ke arah kursi kosong tempat Isak biasa duduk.
Bagas masih menempelkan ponselnya di telinga, tampak mendengarkan instruksi terakhir dari seberang. “Baik, Ibu,” katanya menutup percakapan.
Begitu selesai, ia kembali menatap saya serius. “Jhon, ko ke kantor sekarang. Ibu Kadis tunggu,” katanya tegas.
Saya mengangguk pelan. Jantung saya berdetak agak cepat antara bingung dan penasaran. Tanpa banyak pikir lagi, saya segera bergegas keluar dari ruang VIP, menyalakan motor, dan bersiap menuju kantor dan melaju agak cepat menuju kantor.
Jalanan mulai ramai oleh kendaraan pegawai dan siswa yang berangkat sekolah, bahkan pengemudi yang berlalu lalang tanpa tujuan. Sekitar beberapa menit kemudian, saya tiba di depan pintu kantor, menghela napas, dan bersiap untuk masuk mungkin ada hal penting yang menunggu saya di dalam.
Udara di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah terasa sedikit berbeda. Matahari sudah mulai meninggi, memantulkan cahaya di jendela-jendela kaca kantor yang tampak bersih dan tenang. Dari kejauhan, suara kendaraan lalu lalang terdengar samar, tapi di hati saya, suara itu tertelan oleh detak gugup yang semakin keras.
Saya dan rekan kerja saya, Isak, dipanggil untuk menghadap seorang perempuan yang selama ini hanya kami kenal dari jauh, beliau ialah Ibu Nurhaidah, S.E., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Beliau bukan sekadar pejabat tinggi di instansi kami beliau juga dikenal sebagai “Ibu Gubernur”, sosok yang kata orang tegas, berwibawa, tetapi juga punya hati seorang ibu bagi semua stafnya.
Setelah tiba disana, rekan kerja saya Isak muncul juga sehingga kami berjalan menyusuri lorong menuju ruangannya dengan langkah pelan. Di dada, campuran rasa tegang, hormat, dan penasaran bergolak seperti ombak yang belum menemukan pantainya. Saya tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini mungkin akan menjadi momen yang membekas lama dalam perjalanan karier saya di dunia pendidikan.
Ketika pintu ruangannya terbuka, saya langsung merasakan perubahan suasana. Udara di dalam ruangan terasa tenang, tapi penuh energi. Di atas meja kerja yang rapi, tampak beberapa berkas dan map warna-warni, menandakan aktivitas yang padat. Di balik meja itu, duduklah beliau Ibu Nurhaidah dengan tatapan yang tajam tapi menenangkan.
Tatapan itu seperti mata seorang ibu yang sudah lama mengenal anak-anaknya, tahu mana yang sedang gelisah, mana yang butuh bimbingan. Ketika beliau menatap kami, saya seolah melihat campuran antara ketegasan seorang pemimpin dan kasih seorang pendidik.
“Kamu dua dari Bidang Diksus, kah?” suaranya tenang tapi berwibawa.
Saya dan Isak serempak menjawab, “Benar, Ibu.”
Dalam sekejap, ruang itu terasa seperti ruang kelas kehidupan. Tak ada papan tulis, tak ada buku catatan, tapi setiap kata yang keluar dari mulut beliau terasa seperti pelajaran yang takkan selesai dipelajari.
Ibu memandang kami lama, seolah sedang menilai bukan hanya penampilan luar kami, tapi juga keyakinan di dalam diri kami. Lalu ia berkata dengan nada lembut tapi tegas “Kamu dua jangan mau kalah dengan pendatang. Kalian harus yakin dan mengatakan saya bisa, walaupun tidak tahu.”
Kalimat itu menghentak dada saya. Sederhana, tapi terasa seperti cambuk yang membangunkan semangat yang lama tertidur. Saya menunduk, berusaha mencerna maknanya. Isak di samping saya tampak menelan ludah pelan, seolah juga sedang berusaha mengunci kata-kata itu di dalam hatinya.
Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya nasihat singkat. Tapi bagi saya seorang staf muda dari tanah Papua Tengah kalimat itu adalah mantra keberanian. Di dunia birokrasi yang kadang penuh ketidakpastian dan hierarki yang kaku, kalimat itu terasa seperti kompas yang menunjukkan arah baru.
Ibu Nurhaidah melanjutkan pembicaraan dengan nada lembut. Ia tidak menggurui, tapi menuntun. Seolah sedang memegang tangan kami, membimbing menyeberangi jalan kehidupan yang ramai dan penuh tantangan.
Beliau menjelaskan, percaya diri adalah titik awal dari segala perubahan. Kompetensi bisa dibangun, kemampuan bisa dipelajari, tetapi keyakinan diri harus tumbuh dari dalam.
“Kalau kamu berani berkata ‘saya bisa’, kamu akan cari jalan untuk membuktikannya,” katanya.
Kata-kata itu membuat saya teringat pada banyak momen di kantor saat saya ragu mengerjakan tugas baru, saat menunggu instruksi karena takut salah, atau ketika merasa minder bekerja bersama rekan dari luar Papua yang lebih berpengalaman. Tapi siang itu, semua keraguan itu seolah ditelanjangi oleh satu kalimat pendek: “Saya bisa walaupun tidak tahu.”
Kalimat sederhana ini, bukan sekadar pesan motivasi, tapi panggilan untuk berubah.
Untuk belajar tanpa disuruh, bekerja tanpa takut gagal, dan berani melangkah bahkan ketika jalannya belum jelas.
Setelah pertemuan itu selesai, kami berpamitan dengan menunduk hormat. Ketika langkah kami keluar dari ruangan beliau, saya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada udara baru yang mengisi paru-paru saya udara keberanian.
Di luar ruangan, Isak menatap saya dengan senyum kecil. “Berat, tapi menyejukkan ya,” katanya pelan. Saya mengangguk. Kata-katanya benar. Pertemuan singkat itu seperti sapuan angin yang mengguncang daun, membuat segalanya bergerak, mengingatkan saya bahwa selama ini mungkin saya terlalu sering diam, terlalu sering menunggu.
Sejak hari ini, saya berjanji pada diri sendiri untuk berubah.
Saya akan menguatkan sikap “Saya Bisa”.
Setiap tugas baru yang datang, saya akan menyambutnya dengan keyakinan walau belum tahu caranya, saya akan cari tahu. Saya akan bertanya, membaca, belajar, dan mencoba. Saya akan menjadikan rasa gugup bukan sebagai alasan berhenti, tetapi sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh.
Saya juga akan lebih proaktif berkolaborasi. Tidak lagi menunggu perintah, tetapi bergerak mencari rekan, mitra, dan solusi. Saya ingin menjadi bagian dari generasi baru ASN Papua Tengah yang tidak hanya bekerja, tapi berjuang membangun daerahnya sendiri.
Dan yang paling penting, saya akan mencatat setiap pelajaran dari keberhasilan maupun kesalahan agar pengalaman saya bisa menjadi pembelajaran bersama di bidang Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas.
Sekarang, setiap kali saya kembali ke meja kerja saya, saya selalu teringat pada tatapan Ibu Nurhaidah. Tatapan itu seperti pesan tanpa suara, “Kamu bisa. Asal kamu mau belajar, mau melangkah.”
Saya tidak tahu ke mana jalan ini akan membawa saya. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak lagi takut untuk mencoba. Karena seperti kata beliau dan kini menjadi pegangan saya setiap hari “Kamu harus yakin dan mengatakan: saya bisa, walaupun tidak tahu.”
Kalimat itu kini menjadi nyala kecil di dalam dada saya. Nyala yang akan saya jaga, nyala yang saya harap suatu hari bisa menyalakan semangat anak-anak Papua Tengah, agar mereka pun berani berkata hal yang sama:
“Saya bisa.”