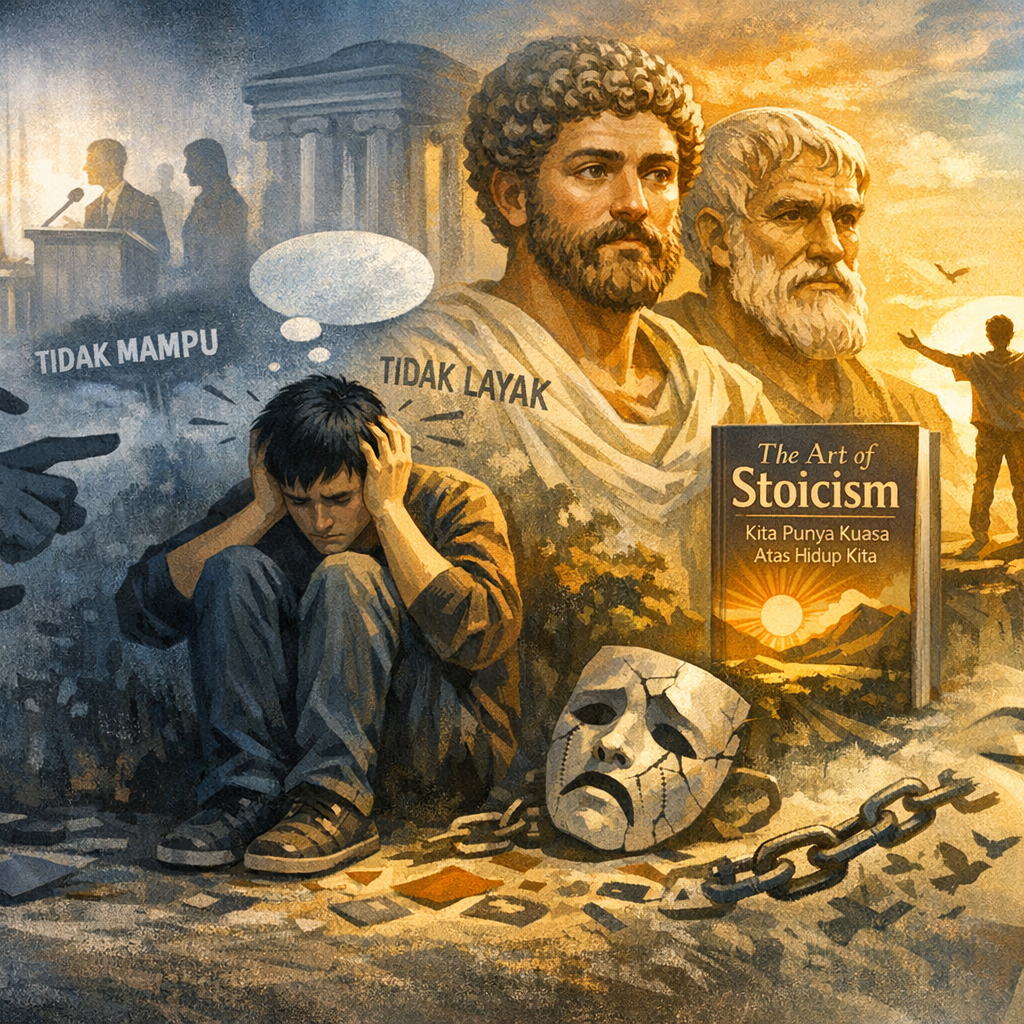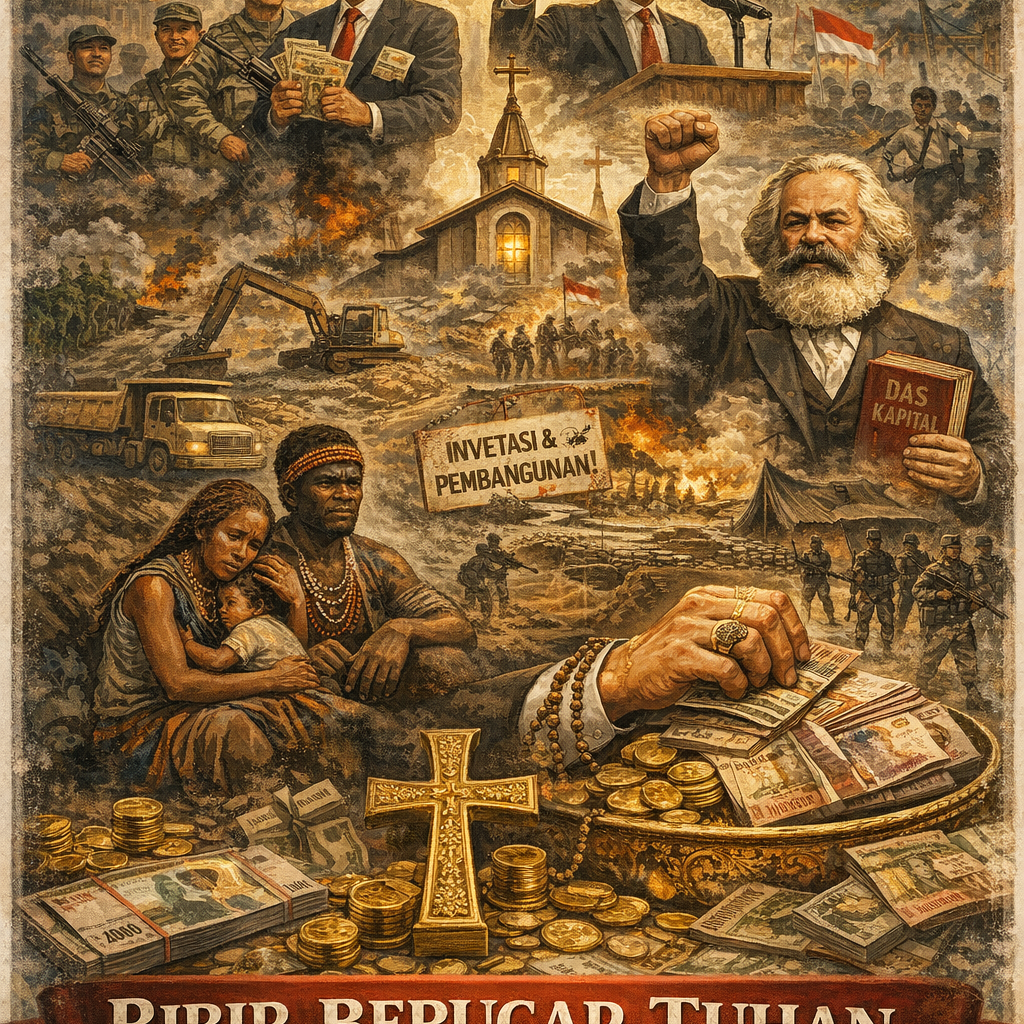Oleh: Jhon Minggus Keiya
Di tengah hiruk-pikuk perayaan Natal di Tanah Papua, sebuah fenomena kultural yang tampak sepele namun sesungguhnya sarat makna sosial kian mengemuka penggunaan rambut palsu atau rambut sambung sebagai bagian dari penampilan. Menjelang hari-hari besar keagamaan dan perayaan sosial lainnya, tidak sedikit orang muda Papua terutama perempuan memilih mengenakan rambut palsu dengan gaya modern sebagai simbol perayaan, kebaruan, dan kepercayaan diri.
Namun, praktik ini tidak dapat dibaca semata-mata sebagai pilihan gaya personal atau ekspresi estetika individual. Fenomena rambut palsu di Papua sesungguhnya menyentuh lapisan yang lebih dalam kebudayaan, identitas, relasi kuasa, bahkan spiritualitas. Rambut palsu, dalam konteks ini, tidak lagi sekadar aksesori mode, melainkan simbol dari pergeseran nilai yang mencerminkan hubungan timpang antara budaya lokal dan budaya luar.
Sekilas, fenomena ini mungkin tampak sebagai tren global yang wajar. Akan tetapi, jika ditelaah lebih jauh, hal ini merepresentasikan proses panjang normalisasi standar kecantikan asing yang secara perlahan menggantikan penghargaan terhadap estetika lokal Papua. Pergeseran ini berlangsung senyap melalui media sosial, industri kecantikan, dan budaya populer menciptakan ilusi bahwa menjadi “modern” berarti menjauh dari identitas sendiri. Di sinilah rambut palsu dapat dibaca sebagai salah satu wajah halus dari penjajahan kebudayaan modern.
Artikel opini ini berangkat dari pertanyaan mendasar, apa yang sesungguhnya terjadi ketika orang Papua merasa perlu menutupi rambut alaminya demi dianggap cantik, modern, dan layak tampil? Pertanyaan ini membawa kita pada pembacaan kritis tentang penjajahan budaya, krisis identitas, serta tantangan spiritualitas orang Papua di era global.
A. Pasar Karang: Ruang Publik, Tubuh, dan Normalisasi Estetika Asing
Hari ini, dari rumah, saya mengendarai motor menuju Pasar Karang untuk membeli ubi kebutuhan dapur yang biasa dan nyaris tanpa muatan reflektif. Namun, setibanya di sana, ruang pasar yang ramai justru menghadirkan sebuah pemandangan yang mengganggu kesadaran saya.
Di kiri dan kanan jalan, anak-anak muda berlalu-lalang. Mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang berlibur Natal, pulang dari berbagai kota studi Jayapura, Nabire, Manokwari, bahkan dari luar Papua menuju kampung halaman di Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Mereka menunggu mobil lintas, naik-turun kendaraan, saling menyapa, tertawa, dan membawa tas-tas perjalanan.
Pasar Karang hari ini menjelma menjadi ruang temu identitas, pertemuan antara kampung dan kota, antara pendidikan dan akar budaya, antara pulang dan menjadi asing. Namun, ada satu hal yang mencolok dan sulit diabaikan yakni hampir seluruh anak muda yang saya lihat menggunakan rambut palsu atau rambut sambung.
Pemandangan ini bukan soal jumlah, melainkan soal pola. Ketika sesuatu tampil seragam di ruang publik, ia berhenti menjadi pilihan individual dan berubah menjadi norma sosial. Rambut palsu di Pasar Karang hari itu tidak lagi hadir sebagai ekspresi personal, tetapi sebagai tanda kepantasan sosial seolah menjadi syarat tak tertulis untuk tampil percaya diri saat pulang kampung.
Pasar, dalam kajian sosiologi budaya, adalah ruang publik tempat nilai-nilai dipertontonkan dan dinormalisasi. Apa yang terlihat “biasa” di pasar sering kali mencerminkan apa yang dianggap wajar dalam masyarakat. Ketika hampir semua anak muda Papua tampil dengan rambut palsu, muncul pertanyaan kritis, apakah ini benar-benar pilihan bebas, atau hasil dari tekanan simbolik yang bekerja secara kolektif?
Pierre Bourdieu menyebut fenomena semacam ini sebagai habitus pola selera dan praktik yang terbentuk melalui proses sosial panjang, bukan keputusan spontan. Rambut palsu, dalam konteks ini, adalah bagian dari habitus modern yang diasosiasikan dengan pendidikan, kemajuan, dan keterbukaan dunia luar. Sebaliknya, rambut keriting alami perlahan disingkirkan dari ruang publik sebagai sesuatu yang kurang pantas dipertontonkan.
Pengalaman di Pasar Karang memperlihatkan bagaimana pendidikan dan mobilitas sosial tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan identitas budaya. Justru sebaliknya, semakin jauh seseorang berjarak dari kampung melalui kota studi, semakin besar tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar estetika dominan.
Frantz Fanon mengingatkan bahwa tubuh orang terjajah sering menjadi lokasi paling awal dan paling dalam dari alienasi. Rambut, sebagai bagian tubuh yang paling terlihat, menjadi objek pertama yang dikoreksi. Apa yang saya lihat di Pasar Karang bukan sekadar anak muda yang sedang berlibur, tetapi generasi yang tubuhnya sedang dinegosiasikan antara menjadi Papua atau menjadi “layak” menurut standar luar.
Edward Said menyebut proses ini sebagai keberlanjutan kolonialisme dalam bentuk representasi. Anak muda Papua tidak dipaksa secara fisik untuk memakai rambut palsu, tetapi dipengaruhi secara simbolik untuk percaya bahwa itulah cara tampil yang pantas, rapi, dan modern. Penjajahan tidak lagi hadir dalam bentuk larangan, tetapi dalam bentuk selera yang dianggap normal.
Ironisnya, semua ini terjadi dalam konteks Natal perayaan kelahiran Kristus yang menekankan kesederhanaan, penerimaan, dan penghargaan terhadap manusia apa adanya. Anak-anak muda ini pulang ke kampung untuk merayakan Natal bersama keluarga, gereja, dan komunitas adat. Namun tubuh mereka justru tampil dengan lapisan estetika yang menyembunyikan identitas alaminya.
Natal yang seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi dengan diri sendiri dan dengan Tuhan, justru memperlihatkan jarak antara iman dan tubuh. Rambut palsu di ruang Natal bukan soal dosa atau larangan, melainkan tanda bahwa spiritualitas orang Papua sedang bergumul dengan rasa tidak cukup terhadap ciptaan Tuhan sendiri.
Apa yang saya saksikan di Pasar Karang bukan anomali, melainkan potret kecil dari realitas yang lebih luas. Rambut palsu menjadi simbol bagaimana generasi muda Papua sedang belajar tampil di dunia sayangnya, sering kali dengan menanggalkan sebagian dari dirinya sendiri.
Pengalaman ini menegaskan bahwa kritik terhadap rambut palsu tidak lahir dari teori semata, tetapi dari realitas sehari-hari yang dapat disaksikan siapa saja yang mau membuka mata. Ia mengajak kita bertanya:
ke mana arah pendidikan, modernitas, dan iman kita jika tubuh sendiri tidak lagi menjadi rumah yang aman bagi identitas Papua?
B. Rambut dan Identitas: Tubuh sebagai Warisan Budaya
Dalam kebudayaan Papua, rambut keriting alami bukan sekadar ciri biologis, melainkan penanda identitas kolektif. Rambut menyimpan makna sosial, simbol kedewasaan, dan relasi dengan komunitas serta alam. Dalam banyak masyarakat adat, tubuh tidak dipahami sebagai milik individual semata, tetapi sebagai bagian dari sejarah bersama.
Namun, globalisasi telah memperkenalkan standar estetika baru yang tidak lahir dari konteks Papua. Media sosial, iklan kecantikan, dan budaya populer mempromosikan rambut lurus, panjang, dan mudah diatur sebagai simbol kecantikan dan kemajuan. Dalam proses ini, rambut keriting orang Papua secara perlahan diposisikan sebagai sesuatu yang “kurang rapi”, “sulit diatur”, bahkan “tidak ideal”.
Pierre Bourdieu menyebut proses ini sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence) sebuah bentuk dominasi yang bekerja secara halus melalui selera, selaras, dan standar yang diterima seolah-olah alamiah (Bourdieu, Distinction, 1984). Ketika standar kecantikan luar diterima tanpa disadari, tubuh orang Papua menjadi medan di mana dominasi itu bekerja.
C. Penjajahan Budaya: Dari Wilayah ke Kesadaran Tubuh
Edward Said, dalam Orientalism (1978), menegaskan bahwa kolonialisme tidak berhenti pada penguasaan tanah dan sumber daya, tetapi berlanjut dalam penguasaan cara berpikir dan cara memandang diri. Penjajahan budaya bekerja melalui representasi: siapa yang dianggap indah, maju, dan beradab dan siapa yang tidak.
Dalam konteks Papua, rambut palsu dapat dibaca sebagai bagian dari proses ini. Budaya luar hadir sebagai tolok ukur ideal, sementara budaya lokal mengalami delegitimasi. Proses ini melahirkan perasaan rendah diri yang dalam analisis Frantz Fanon disebut sebagai alienasi tubuh kolonial.
Dalam Black Skin, White Masks (1952), Fanon menjelaskan bagaimana orang terjajah sering kali terdorong untuk “memakai topeng” budaya penjajah demi memperoleh pengakuan. Tubuh menjadi objek koreksi. Rambut, kulit, bahasa, dan gaya hidup dimodifikasi agar mendekati standar dominan. Dalam kerangka ini, rambut palsu bukan sekadar pilihan estetika, melainkan ekspresi dari luka kolonial yang belum sembuh.
D. Rambut, Iman, dan Krisis Spiritualitas
Mayoritas orang Papua hidup dalam iman Kristen yang kuat. Dalam teologi Kristen, tubuh manusia dipahami sebagai ciptaan Allah yang baik dan bermartabat. Konsep imago Dei (Kejadian 1:27) menegaskan bahwa manusia dalam keberagamannya adalah refleksi kehendak ilahi.
Namun, ketika tubuh tertentu dipandang tidak cukup indah atau layak tanpa modifikasi, muncul ketegangan antara iman dan realitas sosial. Dalam konteks ini, refleksi berikut menjadi penting:
“Memasang rambut palsu merupakan sebuah tindakan yang dipaksakan untuk menolak dan menghina ciptaan Sang Khalik yang sempurna.” _ Keiya Jhon Minggus
Pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai penghakiman moral individual, melainkan kritik terhadap sistem sosial yang memproduksi rasa malu terhadap ciptaan Tuhan sendiri. Teologi pembebasan mengajarkan bahwa tubuh orang tertindas sering menjadi lokasi utama penindasan sekaligus perlawanan (Gutiérrez, 1973).
Dalam teologi kontekstual Papua sebagaimana ditegaskan oleh pemikir-pemikir gereja lokal iman tidak dapat dipisahkan dari pengalaman penindasan, identitas budaya, dan relasi dengan tanah serta tubuh. Menerima tubuh apa adanya menjadi tindakan iman yang membebaskan, bukan sekadar praktik personal, tetapi sikap spiritual dan politis.
Merawat diri, menjaga kebersihan, dan tampil rapi tentu bukan dosa. Namun, perbedaannya terletak pada motivasi dan makna di balik tindakan tersebut. Memperindah ciptaan Tuhan berarti merawat apa yang sudah ada dengan penuh syukur. Sebaliknya, jika seseorang merasa harus menutupi rambut alaminya karena dianggap tidak cukup indah, tidak modern, atau tidak layak, maka persoalannya bukan lagi soal memperindah, melainkan penyangkalan halus terhadap nilai ciptaan itu sendiri.
Dalam iman Kristen, tubuh manusia tidak diciptakan untuk disesuaikan dengan standar dunia, tetapi untuk dimuliakan sebagai karya Allah. Ketika standar kecantikan tertentu membuat kita malu terhadap bentuk alami tubuh sendiri, di situlah muncul krisis spiritual: apakah kita sungguh percaya bahwa ciptaan Tuhan itu baik, atau hanya baik jika sesuai dengan standar tertentu?
Kutipan yang saya sampaikan sebelumnya tidak dimaksudkan untuk menghakimi siapa pun, tetapi untuk menggugat sistem yang memproduksi rasa malu kolektif terhadap tubuh Papua:
“Memasang rambut palsu merupakan sebuah tindakan yang dipaksakan…”
Kata kuncinya adalah “dipaksakan”, bukan sekadar dipilih.
Singkatnya:
-
Hak individu tetap dihormati,
-
tetapi kesadaran kolektif perlu dibangun,
-
agar pilihan tidak lahir dari rasa rendah diri terhadap identitas sendiri.
Kritik ini bukan tentang rambut palsu semata, melainkan tentang keberanian orang Papua untuk berdamai dengan tubuhnya sendiri, tanpa harus merasa kurang, tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar yang tidak lahir dari kebudayaannya.
Kalau semua ini hanya dianggap “kesenangan biasa”, maka kita kehilangan kesempatan untuk membaca luka yang lebih dalam luka sejarah, luka kolonial, dan luka spiritual yang sering kali bersembunyi di balik hal-hal yang tampak sepele.
E. Kebebasan Individu dan Tanggung Jawab Kolektif
Penting untuk ditegaskan bahwa kritik terhadap rambut palsu bukanlah upaya melarang atau menghakimi individu. Yang dipersoalkan adalah struktur nilai yang membuat seseorang merasa harus mengubah dirinya agar diterima. Kebebasan sejati hanya mungkin hadir ketika pilihan diambil tanpa tekanan simbolik dan tanpa rasa malu terhadap identitas sendiri.
Ketika standar kecantikan tunggal mendominasi ruang publik, masyarakat lokal kehilangan kedaulatan budaya. Di sinilah penjajahan budaya bekerja paling efektif, bukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui internalisasi rasa tidak cukup terhadap diri sendiri.
Setiap orang memang memiliki hak atas tubuhnya dan pilihan penampilannya. Tidak ada yang menyangkal kebebasan personal itu. Namun, pembahasan rambut palsu dalam tulisan ini tidak berhenti pada level individu, melainkan bergerak ke level struktural dan kultural.
Masalahnya bukan apakah seseorang boleh memakai rambut palsu, tetapi mengapa begitu banyak orang merasa perlu memakainya agar diterima, dianggap cantik, atau layak tampil di ruang publik. Di sinilah kebebasan individu sering kali beririsan dengan tekanan sosial yang tidak disadari. Ketika sebuah pilihan terasa “bebas” tetapi sebenarnya dibentuk oleh standar kecantikan tunggal yang datang dari luar budaya kita, maka kebebasan itu perlu dikaji secara kritis.
Edward Said dan Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak selalu bekerja dengan paksaan, tetapi melalui normalisasi selera. Sesuatu terasa wajar, padahal itu hasil dari relasi kuasa yang panjang. Jadi kritik ini bukan menyalahkan orang yang memakai, tetapi mempertanyakan sistem nilai yang membuat rambut alami orang Papua sering kali dianggap kurang pantas.
Penutup
Fenomena rambut palsu di Papua adalah cermin dari krisis yang lebih luas yakni krisis identitas, krisis spiritualitas, dan krisis keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ini bukan sekadar persoalan gaya, tetapi persoalan bagaimana orang Papua memandang tubuhnya sebagai ciptaan Tuhan yang utuh atau sebagai objek yang harus disesuaikan dengan standar asing.
Melawan penjajahan budaya tidak berarti menolak modernitas, tetapi memilih secara sadar dengan pijakan budaya dan iman. Merawat rambut alami, memaknainya kembali, dan menampilkannya dengan bangga adalah bentuk perlawanan kultural dan kesaksian spiritual.
Pada akhirnya, mempertahankan identitas bukanlah sikap primitif atau romantik. Hal ini adalah tindakan iman, kesadaran historis, dan keberanian eksistensial orang Papua untuk tetap berdiri tegak sebagai diri sendiri di tengah dunia yang terus berusaha menyeragamkan manusia.
Referensi
- Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press, 1984.
- Fanon, Frantz. Black Skin, White Masks. Grove Press, 1952.
- Said, Edward W. Orientalism. Vintage Books, 1978.
- Gutiérrez, Gustavo. A Theology of Liberation. Orbis Books, 1973.
- Bevans, Stephen B. Models of Contextual Theology. Orbis Books, 2002.
- Dokumen dan refleksi teologi kontekstual Gereja-Gereja di Tanah Papua.